Pengantar ke Masalah
 |
| Gambar dari freepik |
Dalam bahasa Inggris, dikenal dua istilah yaitu "literature" dan "literary" (Shipley, 1962:256). Dalam bahasa Indonesia, kedua istilah tersebut diterjemahkan menjadi "sastra" atau "kesusastraan". Oleh karena itu, istilah "sastra" atau "kesusastraan" mengandung dua pengertian, yaitu:
- Sastra yang bersifat kreatif; berwujud karangan hasil ciptaan para pengarang. Misalnya: novel Kenanga yang ditulis oleh Oka Rusmini, kumpulan cerpen Rumah Bambu yang ditulis oleh Y. B. Mangunwijaya, dan kumpulan puisi Tirani yang ditulis oleh Taufik Ismail.
- Sastra yang bersifat ilmiah; berwujud karangan hasil penelitian para sarjana sastra (peneliti sastra). Misalnya: Prinsip-Prinsip Dasar Sastra yang ditulis oleh Dr. Henry Guntur Taigan, Bentuk Lakon dalam Kesusastraan Indonesia Oleh Boen S. Oemarjati, Tanggapan Dunia Asrul Sani oleh M. S. Hutagalung.
Mengingat sifatnya, kegiatan-kegiatan penyelidikan itu dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: (1) kegiatan penyelidikan yang bersifat teoritis, (2) kegiatan penyelidikan yang bersifat historis, dan (3) kegiatan penyelidikan yang bersifat kritis. Dengan demikian, ilmu sastra berdasarkan sifat-sifat kegiatan penyelidikannya terbagi dalam tiga cabang ilmu, yakni:
-
Ilmu teori sastra adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki dan menghasilkan pengertian-pengertian sastra, hakikat sastra, prinsip-prinsip sastra, latar belakang sastra, jenis-jenis sastra, susunan dalam krya sastra, dan prinsip-prinsip tentang penilaian.Ilmu teori sastra dapat memberi bantuan kepada ilmu sejarah sastras dan ilmu kritik sastra. Ilmu/studi sejarah sastra tidak dapat menjalankan tugasnya denan baik tanpa bantun ilmu teori sastra. Sebab penggolongan-penggolongan ke dalam periode-periode atau ak=ngkatan-angkatan hanya dapat dilakukan dengan pengetahuan tentang teori gaya, wujud, latar belakang, aliran, dan lain sebagainya. Begitu juga halnya dalam studi kritik sastra, seseorang harus mengetahui teori tentang nilai dan ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat-syarat bagi suatu karya sastra yang baik atau bahkan yang agung dalam menilai suatu karya sastra tertentu.
-
Ilmu sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang meneylidiki dan menghasilkan suatu gambaran dan susunan tentang perkembangan kesusastraan sejak awal timbulnya di masa dulu sampai hidupnya di masa sekarang. Dalam sejarah sastra inilah orang dapat melihat timbul dan tenggelamnya suatu jenis sastra (genre) tertentu, bagaimana aliran yang satu mati dan digantikan dengan aliran yang lain, bagaimana aliran-aliran yang tidak sejalan/bertentangan dalam suati kurun waktu tertentu, bagaimana suatu gaya pada suatu waktu dapat merupakan satu mode yang kemudian sangat membosankan dan akhirnya secara mendadak muncul suatu gaya baru.Di atas telah disebutkan bahwa ilmu teori sastra dapat membantu ilmu sejarah sastra. Demikian pula sebaliknya, ilmu sejarah sastra dapat membantu ilmu teori sastra. Hal ini terjadi sebab dalam menyusun teori tentang angkatan ataupun aliran sastra, seseorang tidak dapat lepas dari pandangan terhadap perkembangan sastra secara menyeluruh.Ilmu sejarah sastra dapat berguna pula bagi ilmu kritik sastra. Dalam penyelidikan terhadap keaslian suatu karya sastra -- asli atau tidaknya suatu ungkapan atau karya sastra -- seorang kritikus tidak dapat melepaskan diri dari pengetahuan sejarah sastra.
-
Ilmu kritik sastra adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki karya sastra tertentu secara langsung. Di samping menimbang bernilai atau tidak bernilai suatu karya sastra, penyelidikan ini juga menjernihkan segala macam persoalan yang meliputi karya sastra itu dengan memberikan penafsiran, penjelasan, dan uraian.Ilmu kritik sastra juga membantu ilmu teori sastra dan ilmu sejarah sastra. Ilmu teori sastra tidak dapat menyusun suatu teori tentang teknik cerita yang baik tanpa bantuan kritik terhadap suatu karya sastra tertentu. Begitu pula ilmu sejarah sastra. Tanpa adanya bantuan dari ilmu kritik sastra konkret terhadap karya sastra, maka penyusunan sejarah aliran dan periode akan menjadi sia-sia.
Bedasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga cabang ilmu sastra tersebut saling berhubungan dan saling berjalinan. Bahkan masing-masing tidak dapat berdiri sendiri.
Pengertian Kritik Sastra
Istilah "kritik" berasal dari bahasa yunani: "krites" yang berarti "seorang hakim". "Krites" merupakan kata benda, sedangkan bentuk kata kerjanya adalah "krinein" yang berarti "menghakimi". Selain itu ada pula istilah "kriterion" yang berarti "dasar penghakiman" dan "kritikos" yang berarti "hakim karya sastra".
Istilah "kritik sastra" telah dikenal oleh Bangsa Yunani pada sekitar tahun 500 SM. Kegiatan kritik sastra mula-mula dilakukan oleh Xenophanes dan Heraclitus. Keduanya mengecam Pujangga Agung Homerus yang gemar mengisahkan cerita bohong dan tidak senonoh tentang dewa-dewi. Peristiwa kritik tersebut kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh lain, seperti Aristhophanes (450-285 SM), Plato (427-347 SM), dan Aristoteles (384-322 SM).
Dalam kritiknya, Xenophanes berpendapat bahwa suatu karya sastra haruslah mengandung nilai moral. Sementara kritik dari Aristophanes mulai mempertentangkan antara karya sastra yang bernilai sosial dengan karya sastra yang bernilai seni (Hardjana, 1981:1-2).
Plato berpendapat bahwa karya sastra yang baik haruslah mengandung tiga unsur, yaitu: (1) memberikan ajaran moral yang tinggi, (2) memberikan kenikmatan, dan (3) memberikan ketepatan dalam wujud pengungkapannya (Liaw Yockfang, 1970:2).
Perkembangan kritik sastra dalam kesusastraan Yunani klasik semakin menemukan bentuknya dengan lahirnya buku Peotica karangan Aristoteles. Tulisan itu menjadi sumber pemikiran kesusastraan selanjutnya, terutama sesudah zaman Renaissance di Eropa (Liaw Yockfang, 1970:18).
Buku tentang kritik sastra yang pertama dan lengkap ditulis oleh Julius Caesar Scaliger (1484-1558) berjudul Criticus. Buku ini kemudian menjadi sumber pengertian kritik sastra modern.
Dalam kesusastraan Inggris pada abad ke-17, istilah "critic" merujuk pada orang yang melakukan kritik (kritikus) dan perbuatan kritik itu sendiri (kritik sastra). Kemudian muncul istilah "criticism" yang digunakan pertama kali oleh John Dryden pada tahun 1677. Istilah ini menjadi lebih terpercaya dengan terbitnya buku berjudul The Grounds of Criticism in Poetry pada tahun 1711 oleh John Dennis. Sejak tahun 1711 itu, istilah criticism dianggap lebih tepat dari pada istilah critic. Criticism memiliki arti kecaman dan penilaian terhadap karya sastra. Istilah tersebut mengokohkan ilmu kritik sastra. Sejak abad ke-17, ilmu kritik sastra tumbuh dan berkembang menjadi kegiatan kesusastraan yang mendapat tempat dan tidak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran kesusastraan (Wellek, 1990:22).
Di Indonesia, baik istilah maupun pengertian kritik sastra baru dikenal setelah para sastrawan Indonesia memperoleh pendidikan menurut sistem Eropa pada awal abad ke-20. Sebelum itu, penilaian atas karya sastra dalam kesusastraan daerah biasanya dikaitkan dengan kepercayan agama dan hal mistik. Contohnya pada kesusastraan Melayu: Hamzah Fansuri, seorang ulama dari Baros (Aceh Barat sebelah selatan) dihukum dan puisi-puisinya (antara lain Syair Perahu) dibakar karena ajarn mistik yang terkandung dalam puisi-puisinya bertentangan dengan ajaran Nuruddin Ar Raniri (ulama istana) dan dinilai sangat membahayakan ajaran agama Islam pada umumnya. Penilaian terhadap karya Hamzah Fansuri tersebut bukanlah kritik sastra tetapi lebih tepat disebut sebagai sensor terhadap karya sastra.
Di dalam kesusastraan Indonesia modern, sampai pada masa Pujangga Baru, istilah "kritik sastra" masih dihindari karena memiliki konotasi negatif. Pengarang Pujangga Baru banyak menulis kritik sastra dengan menggunakan istilah lain. Misalnya J. E. Tatengkeng (penyair) menulis kritik sastranya dengan judul Penyelidikan dan Pengakuan; Armijn Pane menulis kritik sastranya berjudul Kesusastraan Lama dan Baru dan sebagainya.
Kedudukan istilah "kritik sastra" dan pengertiannya menjadi kokoh dan mantap di dalam ilmu sastra Indonesia setelah terbitnya buku berjudul Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai karya H. B. Jassin pada tahun 1952. Ada pula berbagai istilah yang sering ditemukan dalam surat kabar dan majalah yang menjadi sinonim dari istilah "kritik sastra" antara lain "penyelidikan", "pengkajian", "telaah", "bahasan", "ulasan", "kupasan", "sorotan", atau "analisa".
Di dalam ilmu sastra Indonesia dikenal beberapa definisi ilmu kritik sastra, di antaranya adalah:
- Hudson (1955:60): Istilah kritik dalam artinya yang tajam adalah penghakiman yang dilakukan oleh seorang kritikus. Kritikus itu dipandang sebagai seorang ahli yang memiliki suatu kepandaian khusus untuk membedah karya sastra, memeriksa karya sastra mengenai kebaikan-kebaikannya dan cacat-cacatnya, serta menyatakan pendapatnya.
- M. H. Abram (1971:35): Kritik sastra adalah studi sastra yang berhubungan dengan pendefisian, pengklasifikasian, analaisis, dan evaluasi karya sastra. Jadi dalam melakukan kritik terhadap sebuah karya sastra, kritikus (peneliti) menetapkan pengertian, menggolongkan, menguraikan atau memecah-mecah sebuah karya sastra ke dalam unsur-unsur pembentuknya (norma-norma), disertai tafsiran-tafsiran, dan akhirnya menerangkan karya tersebut mengenai bagaimana kelebihan-kelebihannya dan kekurangan-kekurangannya dengan alasan-alasan atau komentar-komentar yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Gaylay dan Scott (dalam Liaw Yockfang, 1970): Kritik sastra ialah (1) mencari kesalahan (fauld-finding), (2) memuji (to priase), (3) menilai (to judge), dan (4) membanding (to compaire).
- Stanley Edgar Huyman (dalam Duroche, 1967): Kritik sastra adalah (1) penilaian (evaluation); (2) interpretasi, sebab: a) belum adanya ukuran yang baku, dan b) ukuran itu sendiri tidak dapat disusun; (3) penilaian dan interpretasi.
- Rene Wellek dan Austin Warren (Wellek, 1990): Kritik sastra merupakan studi sastra yang langsung berhubungan dengan karya sastra yang konkret.
Berdasarkan definisi-definisi di atas, kemudian sarjana sastra-sarjana sastra di Indonesia mengemukakan definisi kritik sastra sebagai berikut:
-
H. B. Jassin (1959:45): Kritik sastra itu pertimbangan baik atau buruknya karya sastra, penerangan, dan penghakiman karya sastra.Jadi kritik sastra itu berarti penghakiman terhadap karya sastra. menghakimi itu berarti menentukan baik atau buruknya karya sastra, dalam arti karya sastra tersebut bernilai seni tinggia atau kurang berniali seni.
-
Rachmad Djoko Pradopo (1967: 10): Kritik sastra itu bidang studi sastra untuk menghakimi karya sastra, untuk memberi penilaian dan keputusan mengenai bermutu atau tidaknya karya sastra itu.Dalam kritik sastra, suatu karya sastra itu dianalisis unsur-unsurnya atau norma-normanya, diselidiki, diperiksa satu per satu unsur-unsurnya, kemudian ditentukan berdasarkan "hukum-hukum penilaian" karya sastra, bernilai atau kurang bernilaikah karya sastra itu.
-
Andre Hardjana (1981: xi): Kritik sastra itu hasil usaha pembaca dalam mencari dan menentukan nilai hakiki karya sastra lewat pemahaman dan penafsiran sistematik yang dinyatakan dalam bentuk tertulis.Jadi setiap pembaca sastra dapat menulis kritik sastra, asal betul-betul berminat pada sastra, terlatih kepekaan citanya, dan mendalami serta menilai tinggi pengalaman manusiawinya.Adapun yang dimaksud dengan mendalami serta menilai tinggi pengalaman manusiwinya adalah menunjukkan: a) kerelaan jiwa untuk menyelami dunia karya sastra, b) kemampuan untuk membeda-bedakan pengalaman secara mendasar, dan c) kejernihan budi untuk menentukan macam-macam nilai.
- Henry Guntur Tarigan (1985:188): Kritik sastra ialah pengamatan yang teliti, perbandingan yang tepat serta pertimbangan yang adil terhadap baik-buruknya kualitas, nilai, kebenaran suatu karya sastra.
- "Kritik sastra" yang berarti ilmu kritik sastra (cabang ilmu sastra yang meneliti karya sastra) yang menilai karya sastra, dan mempertimbangkan serta memutuskan apakah karya sastra tersebut memiliki mutu sastra atau tidak.
- "Kritik sastra" yang berarti bentuk laporan (karangan) yang merupakan hasil penelitian pembaca dalam memahami, menafsirkan, dan menilai karya sastra tertentu.











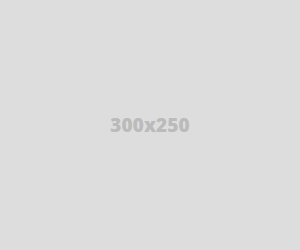
Tidak ada komentar:
Posting Komentar